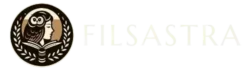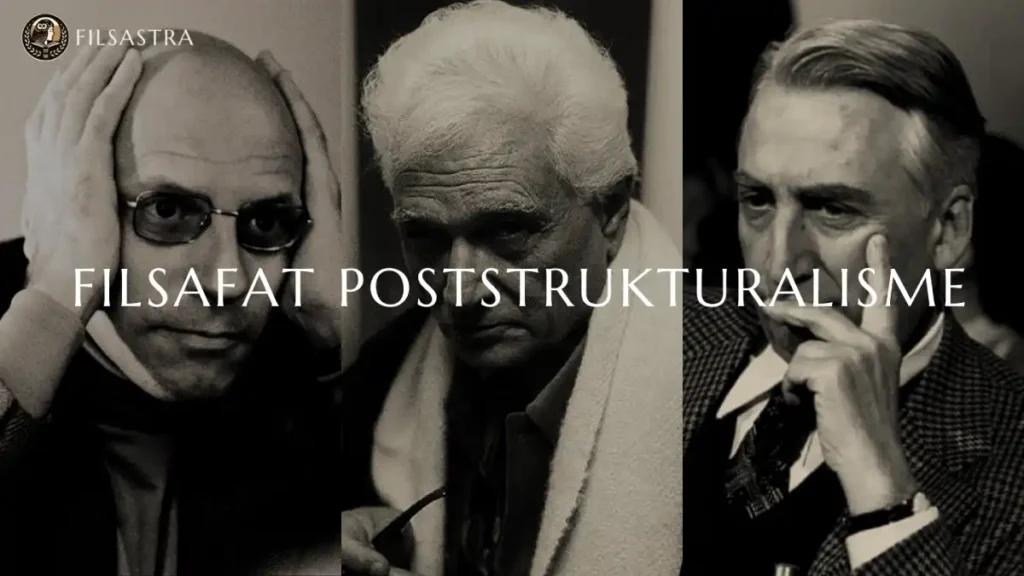
Pernah merasa sangat kesulitan untuk menjelaskan yang kamu rasakan? Mungkin lagi merasa capek, jenuh, terharu, marah, bahagia, tapi tidak ada cara yang benar-benar tepat untuk mengungkapkannya. Seolah kata-kata dan bahasa apapun terlalu sempit untuk menampung kompleksnya emosi dan pikiranmu. Semakin dijelaskan, semakin terasa jauh dari kata yang tepat.
Atau pernah berpikir, kenapa dua orang bisa membaca teks yang sama tapi menangkap makna yang berbeda? Misalnya, mungkin kamu membaca tulisan A dan merasa kamu ‘sudah mengerti’ pesannya, tapi temanmu justru menangkap makna yang berbeda 180 derajat dan berlawanan. Kenapa bisa, ya?
Nah, kalau kamu juga sering bergumul pertanyaan-pertanyaan ini, kemungkinan besar kamu akan tertarik untuk berdiri di gerbang pemikiran poststrukturalisme; sebuah cara pandang yang menggugat kepercayaan bahwa makna itu pasti dan bahasa bisa benar-benar mewakili realitas. Ugh, sounds heavy! Sebenarnya, apa itu poststrukturalisme?
Apa Itu Poststrukturalisme?
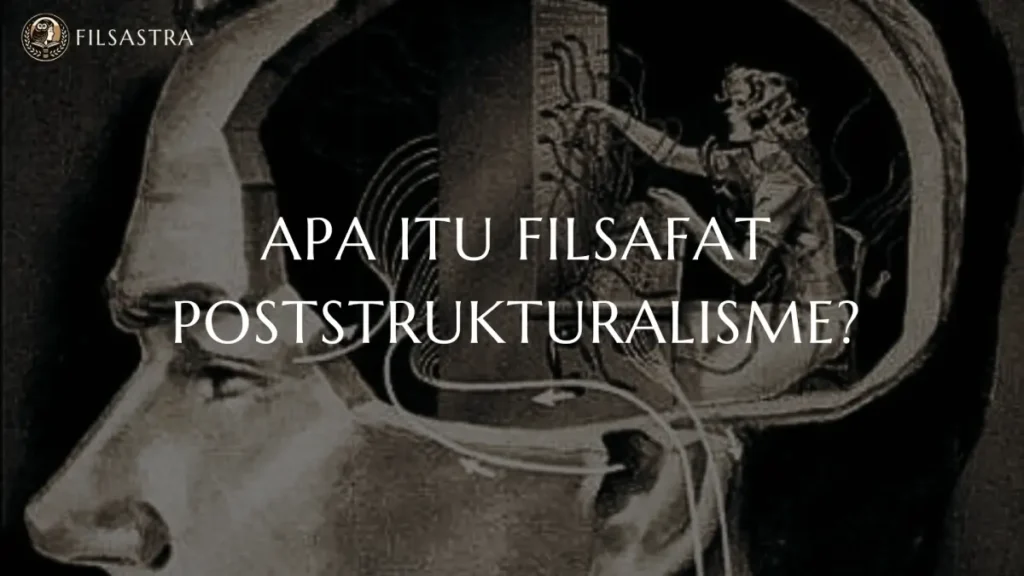
Sederhananya, poststrukturalisme adalah sebuah gerakan pemikiran yang muncul sebagai kritik dan perluasan dari strukturalisme. Kalau strukturalisme yakin bahwa segala hal punya ‘pola tetap’ yang bisa dibaca, poststrukturalisme justru datang untuk mengatakan: “It’s not that simple”.
Bagi pemikiran poststrukturalisme, makna (terkait hal-hal layaknya bahasa, budaya, bahkan identitas) bukanlah sesuatu yang pasti atau telah ‘ditetapkan’. Sebaliknya, makna itu terus berubah tergantung siapa yang melihat, dari mana dilihat, dan kapan melihatnya. Layaknya bersifat ‘cair’ bergantung kuat pada konteks dan relasi.
Simplified: Poststrukturalisme adalah gerakan filsafat yang mempertanyakan apakah struktur-struktur pemaknaan itu benar-benar objektif atau stabil. Sebab, apa yang kita anggap “benar” atau “masuk akal” sering kali bukan karena memang begitu adanya, tapi karena ada sistem yang membentuk cara kita melihatnya.
Contohnya bagaimana?
Misal, pikirkan makna dari satu kata “rumah”. Bagi seseorang, itu bisa berarti rumah secara harfiah, yakni bangunan yang kita tinggali bersama keluarga. Bagi seorang lain, kata itu bisa berarti rasa aman dan hangat. Bagi seorang lainnya lagi, bisa jadi justru mengingatkan pada trauma terentu di masa kecil. Padahal, kata yang digunakan itu satu dan sama yakni: rumah.
Hal semacam inilah yang coba diungkapkan oleh poststrukturalisme: bahwa bahasa dan makna tidak pernah netral dan tidak pernah ditentukan. Tidak ada satu makna tunggal yang “paling benar”. Yang ada hanyalah makna yang terus bergerak, berubah, dinegosiasikan, dan bahkan dipertarungkan; baik dalam percakapan sehari-hari, dalam teks sastra, maupun dalam media.
Perbedaan Poststrukturalisme dan Postmodernisme
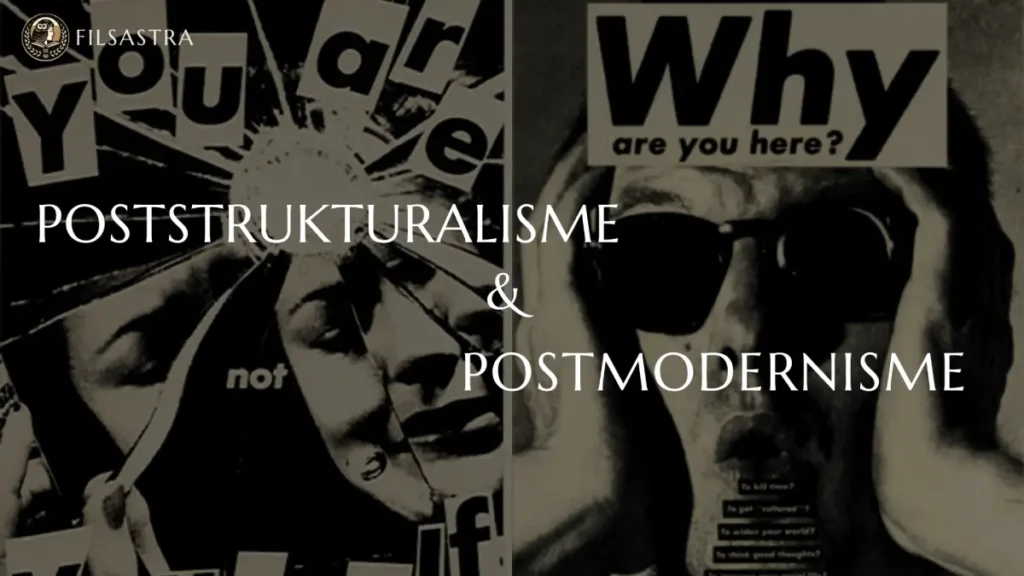
Pembahasan tentang poststrukturalisme sering kali (atau bahkan hampir selalu) dikaitkan dengan postmodernisme. Tak dapat dipungkiri, keduanya memang kerap berjalan beriringan atau bahkan sering tumpang tindih dalam diskusi intelektual. Walau demikian, tetap ada perbedaan mendasar di antara keduanya.
Sederhananya, poststrukturalisme lebih berfokus pada teori dan filsafat bahasa. Pemikiran ini memperdebatkan bagaimana kata-kata bekerja, kenapa satu kata bisa berarti beda bagi orang yang berbeda, dan bagaimana makna bisa berubah tergantung konteks.
Sementara postmodernisme cenderung menyoroti budaya, seni, dan teori sosial. Pemikiran ini sadar dan melihat bagaimana dunia kita dipenuhi simbol serta budaya populer. Postmodernisme tertarik pada film, seni, fashion, arsitektur, dan bagaimana semua itu mencerminkan dunia yang serba plural dan tidak lagi ada “kebenaran tunggal”.
Again, bagaimana contohnya? Ibaratnya begini.
- Poststrukturalisme lebih sibuk membongkar kalimat, tanda baca, dan cara kita berbicara dan berinteraksi, “One word, thousands of interpretations”
- Postmodernisme lebih sibuk mengamati bagaimana gaya hidup dan budaya kita jadi campur aduk dan terasa tidak ada lagi yang asli, “What even is real anymore?”
Menyadari persilangan dan perbedaan kedua pemikiran ini menjadi penting untuk memahami posisi poststrukturalisme dalam lanskap pemikiran kontemporer. Tanpa bisa membedakan keduanya, kita bisa saja terjebak dalam penyederhanaan atau kesalahpahaman saat menilai posisi poststrukturalisme secara keseluruhan.
Tokoh-Tokoh Utama Poststrukturalisme
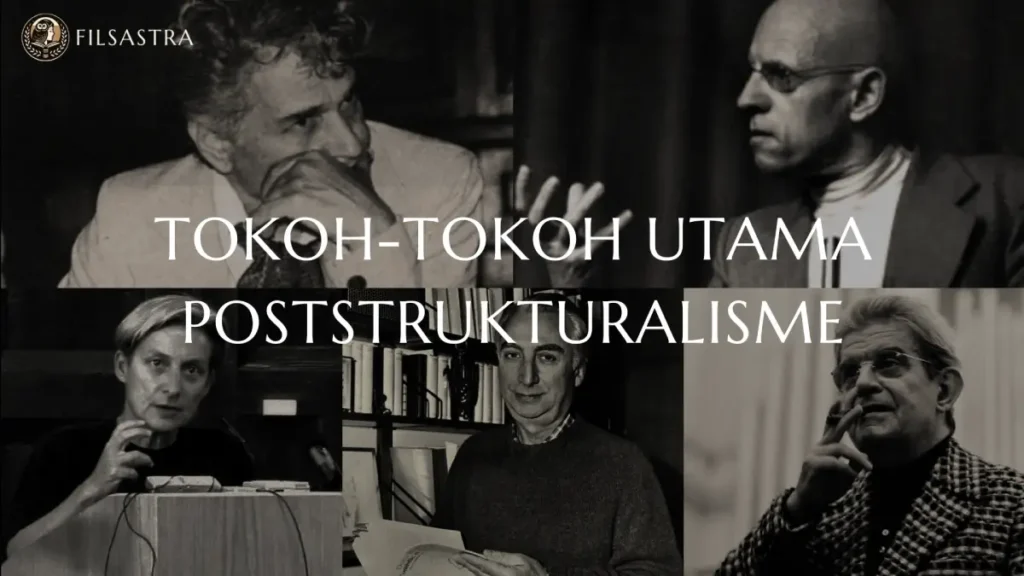
Poststrukturalisme bisa terasa rumit dan memusingkan di awal, tapi mengenal tokoh-tokoh utamanya bisa jadi titik masuk yang menyenangkan dan memperkaya wawasan! Berikut 5 nama penting yang bisa dianggap sebagai “starter pack” untuk memahami poststrukturalisme.
1. Jacques Derrida
Derrida rasanya layak untuk disebut sebagai bapak poststrukturalisme. Tanpa Derrida, poststrukturalisme mungkin takkan pernah lahir. Ia mengguncang dunia teori lewat konsep deconstruction dan différance, dua istilah yang menyatakan satu hal penting: makna tidak pernah tetap.
Menurut Derrida, teks tidak pernah punya pusat makna tetap. Kata-kata hanya merujuk pada kata lain, menciptakan penundaan makna yang tak pernah selesai. Apalagi, makna juga selalu bergeser tergantung siapa yang membaca dan dalam konteks apa.
Karya penting: Of Grammatology (1967)
2. Michel Foucault
Foucault menggeser perhatian dari struktur bahasa ke wacana dan institusi. Ia menunjukkan bahwa apa yang kita anggap sebagai “kebenaran” sebenarnya dibentuk oleh kekuasaan, bukan karena sesuatu itu benar secara objektif.
Lewat studinya tentang penjara, rumah sakit jiwa, sistem pendidikan, hingga seksualitas dan tubuh, Foucault membongkar bagaimana sistem sosial dan politik ikut membentuk pemahaman kita tentang normalitas dan identitas. Pemikiran Foucault sangat membantu poststrukturalisme bergerak dari teori bahasa ke kritik sosial yang nyata.
Karya penting: Discipline and Punish (1975), The History of Sexuality (1976)
3. Roland Barthes
Barthes berperan layaknya jembatan antara strukturalisme dan poststrukturalisme. Dalam esainya yang terkenal, The Death of the Author, ia mengajak kita untuk ‘membunuh penulis’ yang berarti kita harus menolak anggapan bahwa makna teks hanya bisa ditentukan oleh niat penulis saja. Menurut Barthes, membaca adalah proses kreatif di mana pembaca punya peran utama. Teks menjadi ruang terbuka tempat makna bisa lahir dari mana saja.
Karya penting: The Death of the Author (dalam Image–Music–Text, 1977)
4. Jacques Lacan
Lacan membawa psikoanalisis Freud ke ranah linguistik dengan menyatakan bahwa the unconscious is structured like a language. Ketidaksadaran kita (sebagai manusia) bekerja seperti bahasa. Bagaimana maksudnya?
Jadi, Lacan berpendapat bahwa apa yang tersembunyi dalam pikiran kita (seperti hasrat, luka, keinginan, dsb) bukanlah sesuatu yang murni atau bebas dari pengaruh luar. Hal-hal ini dibentuk, dikodekan, dan dimaknai lewat simbol-simbol dalam bahasa.
Menurut Lacan, identitas manusia tidak pernah sepenuhnya utuh. Sejak kecil, kita membentuk citra tentang diri lewat bahasa dan simbol sosial. Proses ini membuat kita menjadi “subjek”, tapi subjek yang selalu “terbelah” karena ada jarak antara apa yang kita inginkan, bagaimana kita dipersepsikan, dan siapa kita sebenarnya.
Konsep-konsep seperti mirror stage (tahap cermin), the Real, the Imaginary, dan the Symbolic menjadi dasar dari bagaimana Lacan memahami pembentukan diri dan subjektivitas. Meskipun istilahnya kadang terdengar rumit, intinya adalah ini: kita tidak pernah benar-benar sepenuhnya “mengenal diri sendiri” karena bahasa dan simbol selalu membatasi kita.
Karya penting: Écrits (1966)
5. Judith Butler
Butler adalah filsuf perempuan feminis dan sarjana studi gender yang karyanya telah memengaruhi filsafat politik, etika, feminisme gelombang ketiga, teori queer, dan teori sastra. Ia mengembangkan ide Foucault dan Derrida dalam isu identitas dan gender.
Butler memperkenalkan gagasan bahwa gender itu performatif, bukan sesuatu yang kita miliki tapi yang kita ‘tampilkan’ berulang kali. Pemikiran Butler berarti bahwa gender dibentuk dan diulang lewat tindakan sosial, bukan berasal dari esensi biologis yang bersifat pasti dan tetap. Butler juga memperlihatkan bagaimana identitas dibentuk oleh norma-norma sosial yang tidak pernah benar-benar stabil.
Karya penting: Gender Trouble (1990)
Kritik dan Kontroversi Seputar Poststrukturalisme

Tentunya, poststrukturalisme tidak pernah lepas dari sorotan kritik dan beragam kontroversi dari kalangan akademisi maupun pemikir publik. Di balik pengaruh intelektualnya yang luas, muncul berbagai perdebatan yang mempertanyakan validitas, dampak, dan bahkan gaya berbahasanya.
Hoaks Sokal “Sokal Affair”
Pada tahun 1996, seorang fisikawan bernama Alan Sokal menulis artikel berjudul “Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity” dan mengirimkannya ke jurnal akademik ternama Social Text. Terdengar rumit, bukan?
Isi artikel tersebut memuat kutipan dari tokoh-tokoh poststrukturalis seperti Derrida dan Foucault namun dengan muatan yang sepenuhnya absurd. Sokal dengan sengaja menulis dengan jargon-jargon ilmiah berat yang obskur dan menulisnya dengan retorika sambil membuat klaim nyeleneh seperti “gravitasi adalah konstruksi sosial”.
Yang anehnya, artikel tersebut lolos dan dipublikasikan sebagai jurnal ilmiah di tahun yang sama tanpa telaah lanjutan ataupun peer review. Padahal, Sokal kemudian mengaku bahwa tulisannya tidak memiliki muatan pikiran atau substansi ilmiah sama sekali!
Fenomena yang disebut sebagai Hoaks Sokal atau Sokal Affair ini menjadi hal monumental untuk melihat kontroversi yang menyelimuti poststrukturalisme. Obskurantisme (atau Obscurantism) seperti ini biasanya menjadi pemicu utama munculnya kritik terhadap poststrukturalisme.
Yang dilakukan Sokal layaknya menunjukkan bahwa jargon postmodern bisa menutupi kekosongan argumen dengan permainan bahasa yang berlebihan. Hoaks Sokal tadi salah satu titik balik kritik terhadap poststrukturalisme, terutama dalam hal obskuritas atau kecenderungan menyembunyikan makna di balik bahasa yang berbelit-belit.
Kritik Rasionalitas dari Habermas dan Chomsky
Membaca karya Derrida, Foucault, apalagi Lacan, memang bukan perkara mudah. Gaya mereka sering dianggap rumit, penuh ambiguitas, dan membingungkan. Tak sedikit yang menilai bahwa mereka sekadar bermain-main dengan bahasa tanpa substansi yang jelas. Kritik seperti ini datang dari para pemikir besar seperti Jürgen Habermas dan Noah Chomsky.
Habermas, misalnya, menilai bahwa poststrukturalisme justru menghambat rasionalitas komunikatif. Padahal, rasionalitas ini penting dan menjadi dasar dalam membangun dialog kritis yang etis dan setara. Tanpa kejelasan makna, Habermas berpendapat bahwa diskusi bisa kehilangan arah dan berubah menjadi sekadar ajang ‘show off’ atau pamer intelektual.
Chomsky bahkan lebih tajam dalam kritiknya. Ia menganggap sebagian besar teks postmodern sebagai “tidak bermakna”, penuh jargon yang tidak bisa diverifikasi, dan menyesatkan secara intelektual. Ia tidak melihat adanya nilai penting dari karya mereka dan justru menyayangkan bagaimana dunia akademik terkecoh oleh gaya retorika yang impresif tapi miskin isi.
Tuduhan Relativisme
Kritik lain yang tak kalah sering muncul adalah kecenderungan relativistik dalam poststrukturalisme. Karena aliran ini menolak makna tunggal dan menganggap kebenaran sebagai sesuatu yang kontekstual, sebagian pihak menilai pendekatan ini bisa meruntuhkan fondasi berpikir kritis. Apa pun bisa diperdebatkan, dan tidak ada pijakan tetap: seolah-olah semua argumen bisa benar, tergantung dari mana dilihat.
Pandangan ini dianggap berbahaya oleh sebagian akademisi karena dapat mengaburkan perbedaan antara analisis kritis yang membangun dan nihilisme yang…. membingungkan.
Para poststrukturalis sendiri tidak tinggal diam terhadap tuduhan-tuduhan ini. Justru bagi tokoh seperti Derrida, ambiguitas adalah bagian dari kejujuran berpikir. Banyak hal yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan gamblang, dan makna bukanlah sesuatu yang statis.
Jadi, kalau kamu merasa tulisan mereka rumit dan sulit dicerna, itu karena topik/realitas yang dibahas memang sangat kompleks dan tak pernah sederhana. Dalam pandangan ini, kerumitan adalah bagian dari usaha memahami dunia secara lebih jujur dan terbuka terhadap banyak kemungkinan.
Relevansi Poststrukturalisme Saat Ini
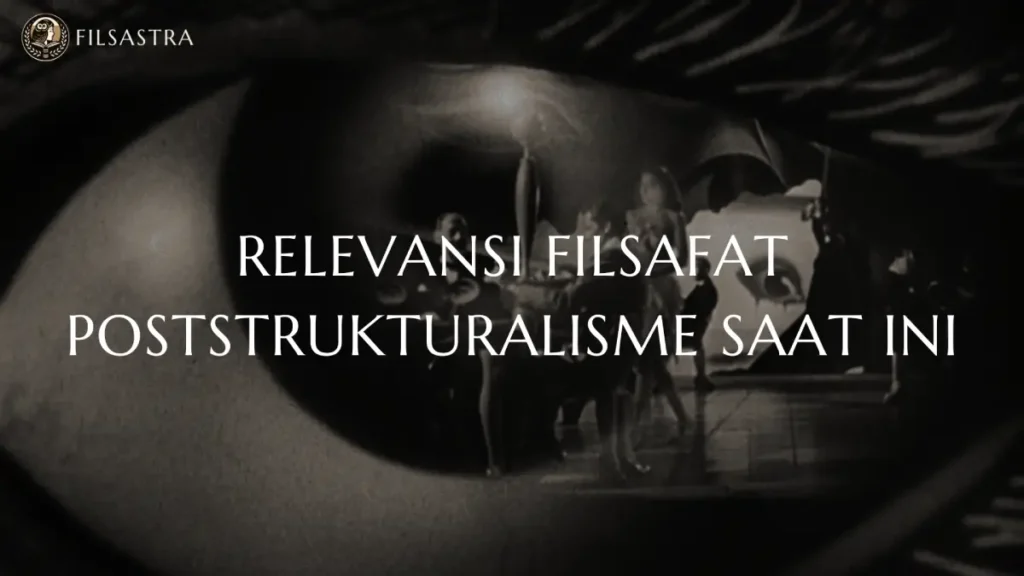
Meskipun lahir dari perdebatan filsafat di abad ke-20, bukan berarti poststrukturalisme berhenti menjadi warisan pemikiran belaka. Justru, banyak gagasannya semakin terasa relevan di zaman sekarang! Terutama saat kita mencoba memahami dunia yang penuh informasi dan identitas yang terus bergeser.
Dalam Kajian Budaya dan Sastra
Di dunia sastra dan kritik budaya, pendekatan poststrukturalis sudah menjadi semacam ‘kacamata utama’. Gagasan bahwa makna tidak tunggal (yang kita kenal lewat Derrida atau Barthes) memungkinkan pembaca untuk menafsirkan karya sastra atau film dengan beragam cara.
Misalnya, satu film bisa dibaca sebagai kritik sosial, narasi trauma, atau bahkan metafora eksistensial, tergantung siapa yang menonton dan dari mana ia melihat. Hal ini membuka ruang dialog yang luas, sekaligus menantang pandangan lama bahwa hanya ada “satu” interpretasi yang sah.
Dalam Media Sosial
Media sosial adalah arena hidup dari ide-ide poststrukturalis. Di platform seperti Instagram atau TikTok, identitas lebih bersifat performatif daripada tetap, layaknya yang dikatakan Judith Butler.
Kita bisa “menjadi” siapa saja, membentuk persona tertentu, menyampaikan narasi diri sesuai konteks, dan berganti-ganti peran sesuai audiens. Di sinilah konsep identitas yang cair dan terbentuk oleh representasi sangat terasa. Apa yang terlihat bukan selalu apa yang “asli” dan mungkin memang tidak ada yang sepenuhnya asli.
Dalam Politik Identitas
Poststrukturalisme juga ikut memengaruhi diskusi seputar politik identitas. Ia memberi alat untuk membongkar bagaimana label seperti “normal”, “perempuan”, “minoritas”, atau “penyimpang” sebenarnya bukan kategori netral, tapi hasil dari wacana sosial dan kekuasaan.
Misalnya, dalam perjuangan kelompok LGBTQ+, poststrukturalisme membantu memperjelas bahwa identitas gender dan orientasi seksual bukan sesuatu yang tetap atau alamiah, tapi dibentuk oleh norma yang bisa dipertanyakan dan dinegosiasikan.
Dalam Kehidupan Sehari-Hari
Dalam keseharian pun, kita sering mengalami realitas yang sesuai dengan cara pandang poststrukturalis. Tidak ada lagi lensa ‘hitam atau putih’. Kita tahu bahwa satu berita bisa diartikan beda oleh dua orang, satu kata bisa bermakna lain tergantung siapa yang mengucapkan, dan satu peristiwa bisa menimbulkan efek yang tak terduga.
Misalnya saat kita mengatakan, “lagi capek”, seseorang bisa mengartikannya sebagai lelah secara fisik dan butuh tidur saja, tapi yang lain mengira kamu sedang burnout secara emosional. Pernah juga maksud kita disalahpahami hanya karena nada pesan di chat terdengar “dingin”, atau ketika melihat satu foto di media sosial yang bisa memicu interpretasi yang berbeda-beda, mau itu pujian atau cemooh.
So, it’s clear.
Poststrukturalisme tidak memberi kita “jawaban tetap”, tapi justru melatih kita untuk membaca dunia dengan lebih peka, kritis, dan terbuka terhadap keragaman makna. Pemikiran ini juga mengajak kita untuk tidak buru-buru menyimpulkan, tidak terjebak pada satu narasi, dan tidak takut mempertanyakan hal-hal yang dianggap pasti.
Di tengah dunia modern yang serba cepat dan penuh hiruk-pikuk informasi seperti sekarang, pemikiran poststrukturalis justru bisa jadi ruang jeda yang mengajak kita berhenti sejenak. Berhenti dan coba untuk melihat ulang, sadar bahwa di balik kata-kata, gambar, atau label identitas, selalu ada lapisan makna yang lebih dalam yang seringkali luput dari perhatian.
Pada akhirnya, membicarakan apa itu poststrukturalisme adalah tentang membuka cara pandang yang lebih reflektif dan sadar konteks. Pemikiran ini mungkin tak memberi jawaban yang pasti dan mudah dimengerti, tapi justru di situlah nilainya: poststrukturalisme mengundang kita untuk terus bertanya, menggali, dan mempertanyakan ulang segala yang kita anggap sudah jelas.
Kalau kamu tertarik menggali lebih dalam seputar filsafat, teori sastra, atau diskusi tentang makna dan identitas di era modern, Filsastra adalah tempat yang tepat untuk memulainya. Jangan ragu untuk baca artikel Filsastra lainnya dan jadi bagian dari komunitas yang merayakan berpikir, membaca lebih banyak, dan hidup lebih sadar makna.
Keep reading, thinking, and understanding.